TERNATE, KOMPAS —Rencana pembatasan hasil tangkapan tuna oleh pemerintah pusat perlu memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya nelayan kecil. Meski bertujuan baik untuk memastikan keberlanjutan populasi tuna, kebijakan itu perlu melihat akar masalah yang lebih mendalam, seperti eksploitasi perikanan dan rantai pasok yang belum optimal.
Peneliti kemaritiman di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dedi Adhuri, mengatakan, langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membatasi jumlah tangkapan tuna hanya menggunakan perhitungan populasi sumber daya ikan atau sering disebut maximum sustainability yield.
Dedi menilai, perlu ada pendekatan baru dengan memasukkan variabel masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya di sektor penangkapan tuna atau opportunity sustainability yield (OSY).
Dia menyebut, di Maluku Utara, khususnya Kota Ternate dan Kabupaten Kepulauan Morotai, nelayan kecil memiliki kerentanan yang tinggi jika kebijakan itu diberlakukan. Berdasarkan survei yang dilakukan BRIN dan University Technology of Sydney tahun 2023, hampir 76 persen nelayan di Ternate bergantung pada penangkapan tuna, sedangkan sisanya menangkap pelagis kecil.
”Pembatasan baik untuk keberlangsungan populasi ikan, tetapi jangan hanya berpaku pada hal itu. Memasukkan masalah kerentanan masyarakat pesisir dalam kebijakan pembatasan adalah keharusan. Dari data yang dikumpulkan, terlihat nelayan paling rentan karena hidup mereka besar bergantung pada tuna,” ucap Dedi saat dihubungi dari Ternate, Selasa (30/1/2024).
Menurut dokumen Kerangka Kerja Strategis Pemanfaatan Perikanan Tuna Tropis di Perairan Indonesia tahun 2023, pembatasan itu dilakukan untuk tuna mata besar (Thunus obessus), tuna sirip kuning (Thunus albacares), dan cakalang (Katsuwonis pelamis).
Pembatasan ini rencananya dilakukan bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Hal tersebut untuk mencegah berkurangnya stok ikan yang bisa menekan hasil tangkapan di masa depan.
Dedi memaparkan, selain kerentanan ekonomi, penerapan kebijakan itu juga perlu memasukkan unsur budaya melaut yang dipegang masyarakat pesisir. Dari hasil survei yang sama ditemukan, 80,7 persen nelayan di Ternate tidak memiliki pekerjaan selain melaut. Menjadi nelayan merupakan bagian dari kehidupan mereka.
Untuk itu, rencana pembatasan harus melihat keberlangsungan budaya ini di masa depan. ”Dampak ke aspek kebutuhan lapangan kerja, perlindungan nelayan miskin, dan hak budaya perlu dimasukkan pula dalam perhitungan pembatasan tangkapan,” ucap Dedi.
Kebijakan pembatasan itu juga diharapkan tidak menekan upaya pemerintah daerah yang sedang mendorong perekonomian nelayan kecil yang bergantung pada sektor perikanan tangkap.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Morotai Yoppy Jutan menjelaskan, di tengah keterbatasan infrastruktur, nilai ekspor tuna dari wilayahnya terus naik. Pada 2023, ekspor perikanan dari Morotai mencapai 1.498 ton, naik dari tahun sebelumnya 1.451 ton.
Hampir separuh dari produk perikanan yang diekspor itu adalah tuna. Menurut Yoppy, hasil perikanan dari wilayah yang berbatasan dengan Filipina itu masih bisa lebih besar lagi. Namun, panjangnya rantai pasok dan belum optimalnya logistik jadi masalah.
Tonase kontainer yang bisa diekspor dari Morotai hanya sebesar 124 ton per bulan. Pengirimannya juga hanya bisa dilakukan sekali dalam 28 hari. Hasil ekspor perikanan dari Morotai masih harus dikirim ke Surabaya sebelum akhirnya tiba di negara tujuan, seperti Vietnam, Jepang, dan Amerika Serikat.
Yoppy menyebut, masih panjangnya rantai distribusi membuat pengusaha kerap tidak mampu menyerap hasil tangkapan nelayan karena masih penuhnya gudang penyimpanan.
Dia menambahkan, pemotongan jalur distribusi dapat dilakukan dengan memanfaatkan rute perjalanan ekspor perikanan dari Bitung, Sulawesi Utara. Melalui Bitung, ekspor tidak perlu melalui Pulau Jawa, tetapi dapat langsung menuju ke Filipina, China, dan Jepang.
”Jika pemerintah bisa menyediakan kapal khusus untuk mengangkut ternak, harusnya untuk perikanan juga bisa. Komitmen ini penting untuk mendorong perikanan. Nelayan di Morotai potensial, jumlahnya 3.743 nelayan, tetapi kapal atau perahu yang tersedia hanya 800-an,” ucapnya.
Eksploitasi perikanan
Direktur Eksekutif Center of Maritime Reform for Humanity Abdul Halim menilai, kebijakan nasional dalam bidang perikanan dan kelautan belum efektif. Bahkan, dia menyebut, kebijakan yang ada bertolak belakang dengan tujuan pemerintah yang ingin mendorong ekonomi biru, tetapi tetap memastikan keberlanjutan sektor perikanan.
Kondisi itu, antara lain, terlihat dari kebijakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengizinkan kapal asing skala industri beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Selain itu, perairan Maluku Utara juga masuk dalam kategori perairan yang dapat menjadi tujuan investasi penanaman modal asing skala industri.
Abdul menyebut, kebijakan penangkapan ikan terukur, yang kini ditunda hingga awal 2025, juga bermasalah karena mengizinkan kapal asing membawa langsung hasil tangkapan ke negara asal. Pengawasan terhadap eksploitasi perikanan pun belum ditegakkan dengan baik. Hasilnya, penangkapan ikan dengan alat tangkap berbahaya masih terus terjadi di Maluku Utara.
Di tingkat provinsi, anggaran pengawasan pun minim. Anggaran pengawasan perikanan di Maluku Utara, misalnya hanya Rp 400 juta per tahun atau setara 16 hari patroli laut. Akibatnya, penegakkan hukum di wilayah laut pun tidak bisa berjalan dengan tegas.
”Kebijakan di tingkat nasional malah bisa menekan upaya pemerintah daerah yang tengah berupaya meningkatkan sektor kelautan dan perikanannya. Masih banyak ironi dalam kebijakan perikanan kita,” ucapnya.
Sumber: https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/30/pembatasan-tangkapan-tuna-perlu-perhatikan-dampak-terhadap-kerentanan-nelayan-kecil?open_from=Search_Result_Page
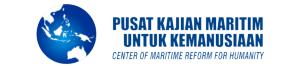
Add a Comment